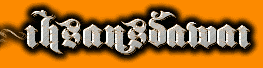Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Saturday, 20 June 2009
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Friday, 19 June 2009
 “Kapan tepatnya kebodohan menjadi sesuatu yang modis? Itu satu hal yang sama sekali tidak bisa kumengerti. Pengkultusan Idiot. Penaikan Derajat pada Orang Bego. Dua novelis paling laris kami, aktris yang payudaranya besar dan orang gila mantan tentara itu, tidak pernah menulis sepatah katapun kau tahu?”
“Cara bicaramu seperti orang yang sudah tua, Roy,” ujarku padanya.”Orang-orang sudah mengeluh soal penurunan standar itu sejak Shaskepeare menulis komedi.”
“Kapan tepatnya kebodohan menjadi sesuatu yang modis? Itu satu hal yang sama sekali tidak bisa kumengerti. Pengkultusan Idiot. Penaikan Derajat pada Orang Bego. Dua novelis paling laris kami, aktris yang payudaranya besar dan orang gila mantan tentara itu, tidak pernah menulis sepatah katapun kau tahu?”
“Cara bicaramu seperti orang yang sudah tua, Roy,” ujarku padanya.”Orang-orang sudah mengeluh soal penurunan standar itu sejak Shaskepeare menulis komedi.”
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
 Betapa pun geniusnya seseorang tapi bila menjelaskan sesuatu hal terkadang kata-kata yang menghiasi bibirnya merujuk ke arah tak pasti. Sebutlah kata-kata “kemungkinan”, “biasanya”, “tidak biasanya”, “sepertinya”, “kayaknya”, dan lain-lain. Kata-kata seperti ini dengan semena-mena digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal dan perihal.Semua orang ingin berbicara, ingin disebut serba tahu, walau hanya sok tahu, ingin disebut paling taat peraturan, taat hukum dan tahu hukum. Sayangnya banyak dari mereka tak tahu diri. Begitulah.
Betapa pun geniusnya seseorang tapi bila menjelaskan sesuatu hal terkadang kata-kata yang menghiasi bibirnya merujuk ke arah tak pasti. Sebutlah kata-kata “kemungkinan”, “biasanya”, “tidak biasanya”, “sepertinya”, “kayaknya”, dan lain-lain. Kata-kata seperti ini dengan semena-mena digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal dan perihal.Semua orang ingin berbicara, ingin disebut serba tahu, walau hanya sok tahu, ingin disebut paling taat peraturan, taat hukum dan tahu hukum. Sayangnya banyak dari mereka tak tahu diri. Begitulah.
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Friday, 12 June 2009
Puisi ini sebenarnya cukup disampaikan oleh bait terakhir saja. Dua bait sebelumnya justru malah menghilangkan maksud yang hendak disampaikan—rumit dan membingungkan.
(Kutemukan bayangmu tak lagi menjelma riuh gemericik hujan)
Bait ini cukup terang. Kau di sana adalah sebuah bayang yang tak lagi menjelma riuh gemericik hujan. Tapi begitu memasuki baris kedua, saya sebagai pembaca mengalami kebingungan
(Seperti seringkali kau menangkap kerinduan di balik rinainya)
Kalimat ini jika berdiri sendiri dia memang bisa dibaca dan terang maknanya. Tetapi jika dikaitkan dengan baris sebelumnya, kata “seperti” di baris kedua ini tidak berkaitan dengan baris yang mendahuluinya. Coba mari kita cermati lagi. Si aku lirik menangkap bayang seseorang yang tidak lagi seperti dulu (riuh gemericik hujan), seperti seseorang tersebut menangkap kerinduan di balik rinainya. Logika kalimat dasar perumpamaan “A seperti B”, atau “sesuatu seperti C”, sama sekali tidak saya temukan dalam 2 kalimat tersebut. Bagi saya, jalinan kalimat tersebut tidak bisa dimengerti. Indah. Tapi tak berarti apa-apa.
(Dan semilir yang setia menggugurkan cemas kering dedaunan Bukan lagi basah yang kian menggenang di balik kelopak mataku)
Kalimat berikutnya juga mengalami hal yang serupa. Saya coba memeriksanya beberapa kali dan mengalami kebingungan yang sama dengan baris sebelumnya.
(Dan semilir yang setia menggugurkan cemas kering dedaunan)
Pertanyaan adalah apanya yang ‘semilir’? Angin? Mungkin karena biasanya kata semilir menyertai angin. Tapi bisa juga tidak. Dan semilir tidak sama dengan angin. Kemudian ‘kecemasan’ yang datang dari mana? ‘Kering dedaunan’ sedang menggambarkan apa? Tentu saja sebagai kalimat yang berdiri sendiri ia tak mengalami persoalan apa-apa. Tetapi begitu dikaitkan dengan baris sebelumnya, dan baris-baris selanjutnya, persoalan pemaknaan mulai muncul. Apalagi dengan tegas penulis mengaitkannya dengan menggunakan kata ’dan’ di awal kalimat. Apa hubungannya dengan 2 kalimat pertama yang juga belum terjelaskan itu?
(Bukan lagi basah yang kian menggenang di balik kelopak mataku)
Kalimat berikutnya nampaknya koheren dengan kalimat sebelumnya. Ia mencoba menerangkan. Tapi berhubung yang diterangkannya masih bermasalah, maka ia jadi tak berarti apa-apa. Kepekatan puitik berbeda dengan kegelapan yang dihasilkan oleh sesat pikir atau cacat logika. Apa yang dimaksud dengan “bukan lagi” di dalam kalimat tersebut? “bukan lagi” tidak ditampilkan dalam kalimat sebelumnya, tapi mewujud di kalimat berikutnya seolah-olah pembaca sudah mengetahui apa yang dimaksud oleh penyairnya. 4 baris di bait pertama ini seperti lanturan yang tak berujung pangkal, tak berkait satu sama lain. Tampaknya saja berkaitan hanya karena mereka dikelompokkan. Tampaknya saja indah, tetapi tak menyampaikan apa-apa.
Bait kedua saya rasa meruntuhkan bait pertama yang sudah runtuh sejak semula.
(Badai yang datang tak getarkan liar ilalang di hatiku Petir bersahutan tak menghapuskan hamparan lapang Satu dua bocah berbasah riang ditingkah derasnya hujan Dan perjalanan kali ini seolah tak menyisakan apa-apa)
“Badai” dan “petir “yang datang dari manakah? Bait pertama bukankah seakan sedang menggambarkan kekeringan, seakan sedang menolak hujan, atau kehilangan hujan? Hujan memang terus disebutkan di bait pertama, tapi dalam keadaan tak lagi berlangsung. Bait kedua sebenarnya selamat dalam hal logika. Kalimat-kalimatnya saling menunjang satu sama lain. Tapi ada kejutan di kalimat terakhir:
(Dan perjalanan kali ini seolah tak menyisakan apa-apa)
O, sedang dalam perjalanan rupanya. “mengejutkan” memang, karena sama sekali tak ada tanda-tanda sebelumnya.
Lalu puisi ini dilanjutkan atau ditutup lagi oleh kalimat:
(: Seperti kepulanganmu yang terlalu deras untuk kurindukan)
Dan ternyata puisi ini adalah perihal kepulangan seseorang yang terlalu deras untuk dirindukan. Tapi terlalu deras di sini tak cukup menjelaskan. Apakah dengan kederasan tersebut dia bisa tetap dirindukan atau tidak.
Puisi bukanlah sejumlah otak-atik bahasa atau kata yang indah. Ia hendak menyampaikan sesuatu. Pertaruhannya adalah bagaimana ia menyampaikan sesuatu itu dengan cara yang luar biasa. Bisa jadi tak indah, tapi ia menyentuh. Puisi hanya cara menyampaikan. Ia bukan tujuan. Puisi juga tak identik dengan berindah-indah, dituliskan dengan kalimat yang rumit, juga metafora yang gelap. Puisi adalah cara kita menyampaikan hal-hal yang kita lihat dan rasakan, bukan sekadar permainan kata belaka. Bisa saja memang kita mencipta puisi lewat permainan kata. Tetapi apa yang tercipta dari permainan tersebut tentu saja harus kita pertanggungjawabkan. Menulis puisi bukan lempar batu sembunyi tangan. Sembunyi di balik kegelapan makna dan ketidakjelasan arti dan maksud.
Mungkin penulis harus mencoba memulai dari yang sederhana saja. Tidak berumit-rumit lalu malah tersesat dan menyesatkan pembaca. Puisi juga bisa sederhana dan apa adanya. Dan keindahan akan lahir dengan sendirinya.

Wednesday, 10 June 2009
 [ Minggu, 31 Mei 2009 ]
Adam, berapa tahun kita terusir? Apa 100, apa 1000, apa 2000 tahun? Kita lupa bukan? Tak apa. Yang pasti, perut kita telah menggelambir. Rambut merontok. Dan sebagian gigi menghitam. Menghitam seperti hati kita yang begitu lama dipanggang oleh matahari yang merendah. Matahari yang menghanguskan ingatan yang berlompatan.
[ Minggu, 31 Mei 2009 ]
Adam, berapa tahun kita terusir? Apa 100, apa 1000, apa 2000 tahun? Kita lupa bukan? Tak apa. Yang pasti, perut kita telah menggelambir. Rambut merontok. Dan sebagian gigi menghitam. Menghitam seperti hati kita yang begitu lama dipanggang oleh matahari yang merendah. Matahari yang menghanguskan ingatan yang berlompatan.
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Friday, 5 June 2009
 Chairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Julai 1922. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Kedua ibu bapanya bercerai, dan ayahnya berkahwin lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil mengikut ibunya ke Jakarta.
Semasa kecil di Medan, Chairil sangat rapat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Chairil. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Chairil melukiskan kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih:
Chairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Julai 1922. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup berantakan. Kedua ibu bapanya bercerai, dan ayahnya berkahwin lagi. Selepas perceraian itu, saat habis SMA, Chairil mengikut ibunya ke Jakarta.
Semasa kecil di Medan, Chairil sangat rapat dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi kesan kepada hidup Chairil. Dalam hidupnya yang amat jarang berduka, salah satu kepedihan terhebat adalah saat neneknya meninggal dunia. Chairil melukiskan kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih:
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Thursday, 4 June 2009
Dalam dunia sastra Indonesia, nama Korrie Layun Rampan tidaklah asing. Dalam usianya yang terbilang belum terlalu sepuh (52 tahun), ia patut disejajarkan dengan sastrawan sekelas Motinggo Busye dan Putu Wijaya dalam hal produktivitas.
Dari tangannya, sudah tercipta ratusan karya sastra baik novel, cerpen, puisi, terjemahan, naskah drama, esai, hingga kritik sastra.
Menurut Maman S Mahayana dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), yang dilakukan Korrie telah menginspirasi sastrawan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Prestasinya bukan hanya karena produktivitasnya, juga kepeloporannya dalam menghasilkan sastra daerah.
”Korrie mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan HB Jassin dalam upayanya melakukan pendokumentasian karya sastra,” ungkap Maman. Kontribusi terbesar Korrie bagi sastra Indonesia, lanjut Maman, adalah pendokumentasian karya sastra angkatan 2000. Ini lantas diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Leksikon Susastra Indonesia dan Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia.
Bekerja sama dengan Pemda Kalimantan Timur, DKJ akhirnya menyediakan ruang terhormat untuk mengangkat karya-karya Korrie, 29-30 September, di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Acara yang digelar berupa pameran, peluncuran buku, pembacaan puisi, dan cerpen serta diskusi tentang karya-karya sang sastrawan bersuara lembut itu.
”Dengan produktivitas, prestasi, dan kontribusi besarnya, kami menganggap Korrie Layun Rampan sudah sepantasnya dihadirkan dalam ajang seperti ini,” kata Maman. Selain itu akan ditampilkan juga pagelaran tarian Dayak yang temanya diangkat dari novel Korrie berjudul Api Awan Asap (1999). Novel ini pernah memenangkan sayembara mengarang roman DKJ pada 1998.
Terhadap penghargaan ini, Korrie berendah hati. ”Sejujurnya saya tidak membutuhkan hal ini, karena tujuan saya berkarya bukanlah untuk mendapatkan penghargaan,” ujarnya. Namun ia juga merasa sangat gembira dan berterima kasih karena karyanya diapresiasi seperti ini.
Korrie Layun Rampan adalah sastrawan besar berdarah Dayak asal Kalimantan Timur. Ia lahir di Samarinda, bertepatan dengan HUT ke-8 RI, yaitu 17 Agustus 1953. Ia memulai karirnya sebagai penulis pada 1971. Hingga saat ini, telah menghasilkan ratusan karya sastra yang beberapa di antaranya meraih penghargaan.
Korrie adalah sastrawan yang menggeluti beragam karya sastra. Hingga saat ini, ia telah menghasilkan 25 antologi cerpen, 10 buah novel, 50 cerita anak, 20 buku esai dan kritik sastra, termasuk 100 terjemahan cerita anak.
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...
Monday, 1 June 2009
 Kehilangan Jejak Sapardian
Kehilangan Jejak Sapardian
KEHILANGAN JEJAK SAPARDIAN PADA SAJAKNYA DI KOMPAS 22 MARET 2009 - SEBILAH PISAU DAPUR YANG KAUBELI DARI PENJAJA YANG SETIDAKNYA SEMINGGU SEKALI MUNCUL BERKELILING DI KOMPLEKS, YANG SELALU BERJALAN MENUNDUK DAN HANYA SESEKALI MENAWARKAN DAGANGANNYA DENGAN SUARA YANG KADANG TERDENGAR KADANG TIDAK, YANG KALAU DITANYA BERAPA HARGANYA PASTI DIKATAKANNYA, “TERSERAH SITU SAJA…” (KADO ULTAH SAPARDI DJOKO DAMONO KE 70)
 Lanjutkan......
Read more...
Lanjutkan......
Read more...